
roxpektif
I and all my writings are to calm the wild inner turmoil within me, maybe with this I will find a little peace :)
12 posts
Latest Posts by roxpektif
Dekonstruksi Mitologi "Calon Arang"

Toeti Heraty (1933–2021): Dekonstruksi Mitologi Calon Arang dalam Perspektif Feminisme
Toeti Heraty adalah seorang filsuf feminis Indonesia yang dalam karyanya Calon Arang mempertanyakan kembali narasi yang telah diwariskan dalam tradisi Jawa-Bali. Calon Arang dikenal sebagai Rangda, janda tua yang dituduh menguasai ilmu hitam, melawan Barong dalam pertunjukan sakral. Rangda melambangkan kekacauan dan energi destruktif, sementara Barong melambangkan keseimbangan dan perlindungan.
Namun, Toeti Heraty menantang narasi ini. Ia mempertanyakan, apakah perempuan seperti Calon Arang benar-benar perempuan jahat? Ataukah ia hanyalah perempuan yang ditindas karena menolak tunduk pada sistem patriarki yang mengekangnya?
Toeti membaca kisah Calon Arang bukan sebagai dongeng tentang penyihir jahat, melainkan sebagai kritik atas narasi misoginis dalam sejarah. Ia menunjukkan bagaimana perempuan yang berpengetahuan dan berdaya selalu dianggap sebagai ancaman dan berbahaya, baik dalam mitos kuno maupun realitas modern.
Ketubuhan Perempuan yang Distigmatisasi
Toeti Heraty juga membongkar bagaimana tubuh perempuan dikonstruksi dalam masyarakat patriarkal. Pengalaman biologi perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, kehilangan keperawanan dilihat sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau diatur sesuai norma sosial yang mengekang.
"Tubuh sehari-hari tiba membawa luka sendiri." Ia menggambarkan menstruasi sebagai luka yang disembunyikan, sebuah pengalaman biologis yang dibebani stigma. "Luka ini tersembunyi dan iklan-iklan gencar dalam upaya mulus menutupi." Kapitalisme pun ikut berperan, dengan iklan yang menampilkan menstruasi dalam bentuk cairan biru, seolah ingin menghapus jejak biologis perempuan.
Keperawanan pun sering kali menjadi standar moral bagi perempuan, sementara laki-laki tidak dikenai standar yang sama. Janda mengalami tekanan sosial yang berbeda dengan duda, mereka dianggap membawa sial atau tidak laku.
"Demikianlah persepsi bahwa perempuanlah kiranya perlu laki-laki daripada sebaliknya." Toeti Heraty menyoroti bahwa dalam banyak kisah, perempuan diposisikan sebagai sosok yang selalu membutuhkan laki-laki. Ini adalahnarasi yang terus direproduksi dalam mitos maupun kehidupan nyata.
Cinta dan Jebakan Biologis
Toeti juga mempertanyakan konsep cinta.
"Cinta sebagai ilusi… ternyata jebakan biologis." Cinta sering kali menjadi alat justifikasi bagi perempuan untuk terjebak dalam sistem patriarkal. Masyarakat mengagungkan cinta, tetapi di balik itu, perempuanlah yang sering kali menanggung konsekuensi biologis dan sosial dari hubungan yang mereka jalani.
"Proyeksi pria yang haus kuasa, membenci dan mendendam sekaligus takut perempuan, itulah misogini." Patriarki tidak hanya membatasi peran perempuan dalam masyarakat, tetapi juga menciptakan narasi yang menakutkan tentang perempuan yang memiliki kekuatan.
Politik, Kekuasaan, dan Perempuan
Toeti Heraty juga menghubungkan kisah Calon Arang dengan realitas politik di Indonesia.
Mpu Baradah datang menemui Sri Mpu Kuturan di Bali yang lebih sakti lagi, untuk diminta persetujuannya atas niat Sang Erlangga menempatkan salah satu putranya pada tahta di Bali. Kisah ini mencerminkan bagaimana kekuasaan diwariskan melalui persekongkolan elite, bukan atas dasar keadilan.
"Bandingkan nepotisme masa kini, kini di Irian, Dili, Aceh… daerah menjadi proyek oleh pemerintah pusat, tidak jelas." Toeti menunjukkan bahwa pola eksploitasi kekuasaan terhadap daerah masih terus berlanjut. Papua, Timor Timur, dan Aceh seringkali hanya menjadi objek kebijakan pusat, tanpa diberikan hak penuh atas diri mereka sendiri.
Di masa kerajaan, upeti diserahkan kepada penguasa pusat. Kini, eksploitasi daerah terjadi dalam bentuk lain. Sumber daya alam dikeruk, sementara kesejahteraan masyarakat lokal tetap tidak merata.
Ratna Manggali: Perempuan dalam Jebakan Patriarki
Kisah Ratna Manggali yang menyerahkan ibunya sendiri kepada Mpu Bahula mencerminkan bagaimana perempuan ditekan untuk tunduk pada kehendak laki-laki, bahkan jika itu berarti mengorbankan sesama perempuan.
Mpu Bahula tidak merayu Ratna Manggali atas dasar cinta, tetapi sebagai strategi politik untuk mencuri kitab suci dan menghancurkan Calon Arang. Perempuan dalam budaya patriarkal sering kali dijadikan alat dan objek, tanpa kuasa penuh atas pilihan mereka sendiri.
Mantra Yang Tak Pernah Padam

Tubuh sehari-hari membawa luka sendiri, menstruasi yang tak boleh disebut, iklan-iklan menyulap darah menjadi biru, seakan tubuh ini bukan miliknya sendiri.
Keperawanan ditakar, menjadi harga dalam bisik-bisik, sementara kehilangan hanya ada pada perempuan. Janda adalah nestapa, duda adalah petualang.
Cinta dipuja sebagai nyala cahaya, tapi siapa yang menanggung beban tubuh? Senggama yang dipaksakan, kehamilan yang dipandang takdir, siapa yang sebenarnya terjebak dalam mitos yang bernama cinta?
Diajarkan bahwa laki-laki harus diutamakan, bahwa istri harus patuh, bahwa ibu bisa dikorbankan demi suami yang bahkan tak mencintainya. Ratna Manggali menyerahkan ibunya sendiri, bukan karena benci, tetapi karena patriarki yang menekan hingga sumsum.
Dulu Calon Arang dituduh perusak, kini perempuan berpengetahuan tetap dicurigai. Di setiap zaman, mereka yang melawan akan terus dibakar, jika bukan dengan api, dengan kata-kata.

The Undying Mantra
Everyday the body carries its own wounds, menstruation that cannot be mentioned, advertisements conjure up blue blood, as if this body is not its own.
Virginity is measured, becomes a price in whispers, while loss is only for women.
Widows are miserable, widowers are adventurers.
Love is worshipped as a flame of light, but who bears the burden of the body?
Forced intercourse, pregnancy that is seen as destiny, who is actually trapped in the myth called love?
Taught that men must be prioritized, that wives must be obedient, that mothers can be sacrificed for husbands who do not even love them.
Ratna Manggali gave up her own mother, not because of hatred, but because of patriarchy that suppresses her to the marrow.
In the past Calon Arang was accused of being a destroyer, now women with knowledge are still suspected.
In every era, it is those who fight will continue to burn, if not by fire, with words.
Dialog Merasa


Perjalanan ke Merasa bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membuatku kembali bertanya tentang hubungan manusia dengan alam, tentang warisan yang ditinggalkan leluhur, dan tentang jejak yang ingin ditinggalkan di dunia ini.
Aku datang membawa pertanyaan, kegelisahan, dan dorongan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Dayak Kenyah memaknai hidup mereka, sebuah kehidupan yang berpijak pada keseimbangan dengan alam, bukan eksploitasi atasnya.


Merasa menyambutku dengan lanskap yang nyaris mistis—tebing karst yang menjulang, Sungai Kelay yang mengalir tenang, kebun kakao yang subur, dan di dalam rimbanya, orang utan yang berjuang untuk kembali ke rumahnya.
Salah satu titik perenunganku terjadi di Batu Lungun, makam leluhur masyarakat Dayak yang berusia lebih dari tiga abad. Makam-makam ini, yang dahulu menjadi tempat peristirahatan jasad dan benda-benda peninggalan leluhur, kini tak lagi utuh. Aku berdiri di depan tebing yang menyimpan sejarah panjang, menyadari bahwa waktu dan tangan-tangan manusia telah banyak merenggutnya. Lungun yang kosong itu bukan sekadar kehilangan artefak fisik, tetapi juga kehilangan makna, kehilangan penghormatan pada mereka yang datang sebelum kita.
Di depan Lungun, aku merasakan suatu keheningan yang berat. Seperti ada suara-suara yang mencoba berbicara dari masa lalu, mencoba mengingatkan kita bahwa tanah yang kita pijak bukanlah sekadar ruang kosong, tetapi ruang yang penuh dengan cerita, dengan roh, dengan sejarah yang masih bernapas. Aku bertanya-tanya, jika leluhur yang dimakamkan di sini masih bisa berbicara, apa yang akan mereka katakan tentang dunia yang kita tinggali sekarang?



Lalu aku kembali menyusur Sungai Kelay menuju kebun kakao, di mana masyarakat Kampung Merasa bekerja setiap hari. Di sini, tanah bukan sekadar lahan produksi, tetapi bagian dari hidup yang dirawat dan dipahami. Tidak ada keserakahan, tidak ada dominasi atas alam, hanya keterhubungan yang terjalin dalam siklus yang mereka jaga bersama.
Di pondok kecil di antara pohon kakao, aku duduk mendengarkan para petani bercerita. Ada sesuatu yang begitu intim dalam momen ini—sebuah rasa kebersamaan yang muncul hanya ketika seseorang benar-benar hadir, mendengar tanpa tergesa, melihat tanpa menghakimi.
Puncak perjalananku adalah saat aku berkunjung ke Pulau Bawan, menyaksikan orang utan yang sedang dalam masa rehabilitasi sebelum kembali ke hutan. Aku melihat mereka bergerak, memanjat, dan perlahan-lahan belajar kembali bagaimana menjadi bagian dari alam. Ada harapan di sana, tetapi juga kesedihan. Aku memikirkan bagaimana manusia sering kali menjadi penyebab kehancuran, tetapi juga satu-satunya yang bisa memulihkan. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku bagian dari kehancuran itu? Ataukah aku bisa menjadi bagian dari pemulihan?

Pada dini hari setelah kembali dari perjalanan ini, aku terbangun dan menatap bulan yang perlahan meninggalkan malam. Kali ini, aku tidak merasa kosong. Aku membawa pulang sesuatu dari Kampung Merasa. Sebuah pemahaman baru tentang apa artinya hidup, tentang bagaimana kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari kehancuran, tetapi bagian dari upaya memulihkan.
Merasa mengingatkanku bahwa di tengah dunia yang serba cepat ini, ada ruang bagi keheningan, bagi hubungan yang lebih dalam dengan alam, bagi penghormatan terhadap sejarah. Aku tahu bahwa aku tidak akan bisa hidup sepenuhnya seperti masyarakat Dayak Kenyah, tetapi aku bisa belajar dari mereka. Aku bisa mengingat bahwa keberlanjutan bukan sekadar inovasi, tetapi juga penghormatan terhadap yang telah ada sebelum kita.
Pasrah (2023)

Ketika akhir dari gelisah adalah menyerah, dan pasrah menjelma menjadi sisa dari harapan yang nyaris musnah.
Di dalam kegelisahan yang nyaris menggilakan, aku mencari jalan keluar dari proses menyembah kekosongan. Memasrahkan diri pada dunia yang penuh ragu, ikut-ikutan menjadi bagian dari orang-orang yang beriktikad menuju hakikat Tuhan.
Namun, apakah benar aku sedang menuju hakikat? Atau hanya mengikuti parade wajah-wajah yang tersenyum? Tetapi, apakah ini ikhlas, atau hanya topeng lain yang kubuat sendiri?
Merasa telah menemukan jalan, padahal mungkin aku hanya mengikuti arus, terjebak dalam ketakutan, dalam keinginan untuk terlihat tenang.
Apakah aku pasrah, atau hanya menyerah dalam kepura-puraan? Di dini hari ini, aku bertanya pada bayangan sendiri.
Badut Congkak (2023)

(Badut tidak sekadar penghibur di panggung sirkus atau pesta ulang tahun, tetapi sebagai simbol, sebagai metafora)
Badut, dalam ingatan banyak orang, adalah tawa yang meledak di antara permainan warna, wajah yang dilukis riang. Namun, badut bukan hanya peran dalam hiburan, melainkan topeng yang menutupi sesuatu yang lebih dalam. Ia adalah seseorang yang menyembunyikan identitasnya, mengubur sisi lain dari dirinya di balik riasan tebal dan senyum yang dipaksakan.
Seberapa banyak manusia menjalani hidup sebagai badut? Memainkan karakter yang diharapkan, bukan yang sebenarnya? Menjadi riang di luar, tetapi di dalamnya ada kekosongan, ada sunyi yang tak tersentuh?
Senyumnya sumringah, tawanya renyah terkadang terbahak. Padahal menyimpan duka dan luka yang mendalam.
Mari kita melihat lebih dalam, melampaui tawa yang terpampang, menembus lapisan-lapisan yang menutupi. Lihatlah kepedihan di balik warna-warninya.
Mungkin saja justru menemukan diri kita sendiri dalam senyumnya yang dipalsukan.
Karena setiap orang menyimpan badut dalam dirinya.
Dini Hari (2022)

Dalam diam dan sunyi dini hari. Saat tubuh terbangun di antara bayang-bayang malam, dan bulan yang perlahan surut menuju ujung langit.
Di sela tarikan napas yang samar, kenangan bertahun-tahun lalu bergetar kembali. Malam-malam ketika aku mencari, menyelami ruang hening yang tidak memberi jawaban.
Aku yang dulu pernah menyembah kekosongan, berharap menemukan sesuatu di dalam kehampaan.
Di dini hari seperti ini, aku belajar membaca ulang jejak diri, mengurai yang pernah tersimpan rapat dalam diam dan sunyi.
Mungkin bulan akan segera pergi, tapi cahayanya selalu meninggalkan tanda, seperti ingatan yang tak pernah benar-benar hilang.
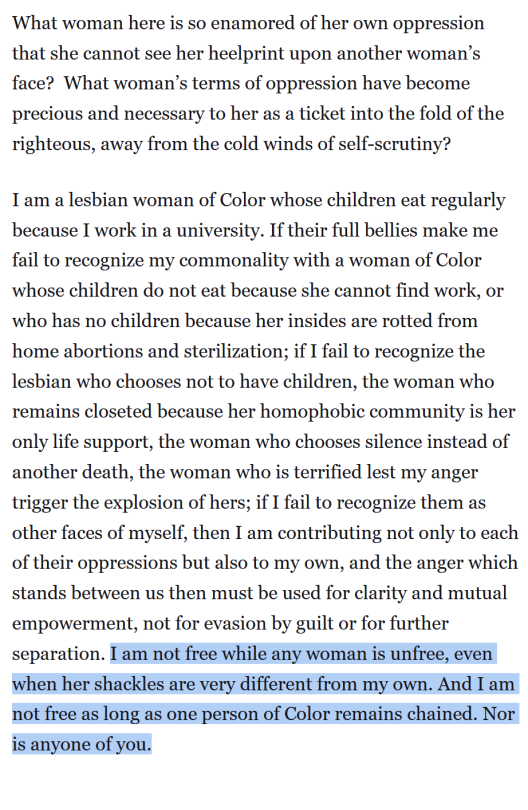
Audre Lorde, from "The Uses of Anger: Women Responding to Racism" (1981)
Melebur di Antara Dua Dunia

Aku sering merasa berada di persimpangan dua dunia yang tampak bertolak belakang. Di satu sisi, peranku sebagai pengajar Al-Qur'an membentuk persepsi tertentu di mata masyarakat. Aku kerap dilihat sebagai sosok yang alim, religius, dan terikat pada norma-norma syar'i—dari cara berpakaian hingga cara bertutur. Namun, di sisi lain, dunia seni rupa yang kujalani justru menawarkan kebebasan berekspresi, eksperimentasi, dan interpretasi yang luas—sesuatu yang jauh dari stereotip seorang qoriah.
Dua dunia ini sering kali membuatku merasa harus "memilih" cara menampilkan diriku di hadapan orang lain, seolah keduanya tidak bisa berjalan beriringan. Realitas ini mengajakku untuk merenung: bagaimana aku bisa menempatkan diriku dengan percaya diri di antara dua dunia yang berbeda ini? Bagaimana aku dapat mengintegrasikan keduanya tanpa harus mengorbankan salah satunya?
Sebagai qoriah, aku sering dianggap sebagai representasi moralitas dalam komunitas. Persepsi ini membuat masyarakat cenderung mengawasi penampilanku dengan harapan agar aku senantiasa mematuhi standar tertentu. Namun, di sisi lain, seni rupa—yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku—menawarkan kebebasan dan ruang ekspresi yang lebih cair. Dalam seni, aku menemukan cara untuk menyalurkan keresahan, kegelisahan, bahkan ide-ide yang mungkin tidak selalu bisa kusampaikan melalui peranku sebagai qoriah. Dunia seni membuka mataku pada berbagai perspektif baru, yang terkadang membuatku mempertanyakan batasan-batasan yang selama ini melekat pada diriku.
Aku ingin menjadi qoriah yang tetap membawa pesan spiritualitas, sekaligus menjadi seniman yang bebas berekspresi tanpa merasa terbelenggu oleh ekspektasi tertentu. Aku ingin menemukan cara untuk menyelaraskan kedua peran ini, sehingga bukan hanya saling melengkapi, tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang memberdayakan—bagi diriku sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarku.
"Melukis Tuhan"
Tulisan ini merupakan refleksi dari buku Memburu Muhammad karya Feby Indirani—sebuah buku yang menggugah dan mengaktifkan kembali caraku memandang agama sebagai jalan hidup.
Dalam kemasygulannya, Pramana tercenung menatap gulungan kanvas, krayon yang berserakan dan aroma khas cat minyak menguar di sekitarnya. Suara-suara bertanya “seperti apakah Tuhanmu?” terus mengusiknya. Berhari-hari ia hidup dalam bayang-bayang pertanyaan itu. Ia bingung menjelmakan sosok Tuhan.
Namun, tanpa ia sadari, Tuhan telah hadir dalam wujud seorang gadis pengemis berkaus lusuh yang mengais-ngais tong sampah mencari sisa makanan, seorang ibu paruh baya berkerudung yang mendorong gerobak dagangannya, lelaki pemulung muda yang memunguti gelas dan botol plastik, dan seekor anjing kampung kudisan yang mengendus-ngendus kakinya.
Tuhan tidak hanya hadir dalam bentuk yang sakral dan abstrak, tetapi juga dalam pengalaman hidup, dalam tubuh-tubuh yang berjuang melawan ketakadilan.
Kamu juga bisa melihat Tuhan pada angin sepoi-sepoi yang menenangkan pikiran yang gelisah dan sungai yang mengalir tanpa henti, memberi kehidupan bagi banyak orang.
Apakah pencarian spiritual kita selama ini terlalu terikat pada simbol-simbol yang jauh, sementara Tuhan justru hadir dalam kemanusiaan yang nyata?
Apakah pencarian Tuhan harus selalu bersifat mistis, atau justru bisa ditemukan dalam tindakan welas asih terhadap sesama?

"bulan timbul"
Lihat map, tahu jalan
Lihat kompas, tahu arah
Lihat jam, tahu waktu
Lihat bulan? tahu arus

Perjalanan residensi ini membawa aku lebih dari sekedar penelitian, ia menjadi refleksi pribadi yang mendalam. Aku memulai dengan tujuan sederhana; memahami hubungan bapak dengan sungai dan laut, yang telah menjadi bagian penting dan urat nadi di hidupnya. Rasa penasaranku terhadap pengalamannya membawaku ke semesta yang lebih besar. Dari sungai, aku akhirnya bisa mengenal Bapak lebih dalam. Aku menemukan pengetahuan lokal yang berakar pada kearifan alam, kisah keluarga yang terukir dalam sejarah migrasi, dan bagaimana keduanya mempengaruhi identitasku sebagai individu yang terhubung dengan masa lalu dan lingkungan tempat aku tumbuh.
Bapak adalah seorang pria sederhana dan cukup religius. Sejak kecil ia menjadi bagian integral dari laut. Bapak adalah seorang anak buah kapal selama lebih dari dua dekade, menjalani kehidupannya di laut dan sungai, menjadikannya saksi bisu dan pelaku aktif dari dinamika alam yang terus berubah. Sungai dan laut bukan sekadar medium transportasi baginya, tetapi juga adalah guru yang sabar, mengajarkan pelajaran yang berharga tentang ritme alam. Dalam narasi ini, aku menelusuri bagaimana bapak dan komunitas lokalnya meniti arus kehidupan dan membagikan pengetahuannya seputar sungai dan laut.
Sungai Sebagai Guru Kehidupan
Dari obrolan bersama bapak, aku juga mengetahui beberapa peristiwa penting dan langka yang pernah terjadi pada masa lampau. Bapak berkisah, pada tahun 1980-an wilayah Berau mengalami kemarau panjang hingga berminggu-minggu lamanya. Hal ini menyebabkan Sungai Kelay mengalami perubahan drastis selama kurang lebih satu minggu. Bapak bercerita, bahwa air sungai yang biasanya tawar menjadi air payau (kondisi dimana air tawar bercampur dengan air asin). Hal ini pula ditandai dengan air yang berkilau, kilauan ini hanya bisa dilihat ketika bulan gelap. Bapak dan komunitas lokalnya yang sangat bergantung dengan sungai, kemudian mencari cara lain untuk mengatasi masalah ketersediaan air. Perubahan air tawar menjadi payau menegaskan betapa besarnya ketergantungan manusia pada sumber daya alam yang stabil. Dan juga ini menunjukkan kemampuan manusia dalam beradaptasi dengan perubahan.
Bapak juga menceritakan tentang hilangnya beberapa makam dan munculnya tengkorak-tengkorak ke permukaan tanah. Hal ini terjadi karena peristiwa erosi tanah yang terjadi di Kampung Sukan sekitar tahun 1990-an. Erosi tanah yang menghilangkan makam menunjukkan bahwa alam memiliki kekuatan untuk mengubah, bahkan menghancurkan warisan manusia. Makam adalah simbol keberadaan nenek moyang, dan kehilangannya bisa diartikan sebagai hilangnya ikatan sejarah dengan masa lalu. Peristiwa ini mengingatkanku bahwa alam tidak hanya menjadi tempat hidup, tetapi juga tempat peristirahatan terakhir yang harus dihormati. Kehilangan makam dan munculnya tengkorak di permukaan tanah memberikan makna spiritual yang mendalam. Hilangnya makam tidak hanya menggugah rasa kehilangan, tetapi juga menjadi momen refleksi untuk lebih menghargai warisan budaya dan leluhur.
Melalui residensi ini, aku tidak hanya belajar tentang cerita lama tetapi juga tentang refleksi mendalam terhadap kehidupan, alam, dan hubungan manusia dengan masa lalu. Kisah bapak tentang perubahan air Sungai Kelay dan erosi di Kampung Sukan menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, memberi pelajaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghormati warisan leluhur.
Sebagai generasi penerus, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa cerita-cerita ini terus hidup, menjadi pengingat untuk selalu hidup selaras dengan alam dan menghormati jejak sejarah yang telah ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelum kita.
Kisah Buyut: Migrasi dari Donggala ke Kalimantan Timur
Perbincangan bersama bapak juga membawa aku kembali ke akar sejarah keluarga. Aku mulai memahami bagaimana perpindahan, adaptasi dan perjuangan buyut ku hingga membentuk identitas keluarga kami. Migrasi buyutku dari Donggala, Sulawesi Tengah ke pesisir Kalimantan Timur bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual yang melibatkan keputusan penting dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian.
Buyutku, Wa’ Sunding, adalah seorang pelaut ulung yang berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah. Sekitar tahun 1910/1920-an, Wa’ Sunding bersama anak dan saudaranya berpindah dari Donggala, Sulawesi Tengah ke pesisir pantai Kalimantan Timur. Berbekal pengetahuan lokal seperti membaca arah angin, pembacaan pasang surut air laut dengan pengamatan bulan dan mengenali bintang sebagai panduan navigasi, mereka kemudian mantap berpindah dan membuat pemukiman baru di pesisir pantai Kalimantan Timur yang mereka beri nama Ulingan. Dengan kearifan lokal yang dibawa dari Donggala, mereka berhasil beradaptasi dengan lingkungan baru dan membangun kehidupan yang stabil.
Salah satu pengetahuan lokal yang diwariskan Wa’ Sunding adalah kemampuan membaca pasang surut air laut melalui pengamatan bulan. Pengetahuan ini sangat penting, terutama untuk mereka yang bergantung pada sungai dan laut. Alam punya ritmenya sendiri, dan bulan salah satu petunjuk. Jika kita melihat bulan di langit, kita bisa mengetahui kondisi air. Dengan memahami pola pasang surut air terkait pengamatan bulan, kita bisa memperkirakan kapan air pasang dan surut. Kita juga bisa memperhatikan gerakan air lebih cepat atau lambat yang mengindikasikan perubahan pasang surut air. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk menjaga keselamatan.
Kemudian sekitar tahun 1980-an, bapak dan kakekku berpindah dari Ulingan ke Kota Tanjung Redeb. Dan membuat pemukiman baru di kawasan Sungai Kelay tepatnya di kawasan Jalan Milono.
Pengetahuan lokal yang diwariskan Wa’ Sunding menjadi bukti betapa berharganya tradisi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Hal ini mendorong aku untuk mendokumentasikan tradisi tersebut dalam bentuk kalender fase bulan serta pasang surut airnya. Kalender ini tidak hanya berguna bagi keluarga ku, tetapi juga dapat membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas di laut dan sungai.

Warisan Buyut: Kalender Bulan Timbul
Pengetahuan tentang pasang surut air melalui pengamatan bulan tidak hanya menjadi alat untuk bertahan hidup tetapi juga simbol kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Aku masih ingat dengan jelas ketika pertama kali mengetahui bahwa pasang surut air dapat diprediksi melalui pengamatan bulan.
Hari itu, aku sedang duduk bersama bapak, mendengar cerita tentang aktivitasnya di masa lalu. Bapak mulai berbicara tentang bagaimana kakek buyut kami menggunakan bulan sebagai panduan untuk memahami pasang surut air sungai dan laut.
Awalnya, aku sangat kebingungan sekaligus antusias dan merasa tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Kemudian, bapak menjelaskan dengan detail bagaimana fase bulan seperti bulan baru, bulan seperempat, dan bulan purnama dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya air. Aku tertegun, terdiam, namun terpesona. Ilmu ini terdengar begitu sederhana tetapi sekaligus kompleks.
Setelah mendengar cerita itu, aku meminta bapak untuk memberikan lebih banyak detail. Ia dengan sabar menjelaskan pola-pola pasang surut yang ia pelajari dari kakek buyut serta istilah-istilah tradisional untuk mengetahui kondisi air. Aku mulai mencatat semua informasi ini dalam buku catatan kecil milikku.
Dari informasi tersebut, aku menemukan fakta bahwa warisan pengetahuan lokal dan tradisional ini tidak hanya bertahan tetapi juga tervalidasi oleh sains. Artikel-artikel ilmiah menjelaskan bahwa pasang surut air dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi bulan.
Istilah “bulan timbul” digunakan oleh bapak untuk menunjukkan usia bulan. Istilah ini memiliki kemiripan dengan istilah astronomi yang digunakan untuk menjelaskan fase bulan. Menurut bapak, bulan timbul 1 mengacu pada bulan baru, yaitu ketika bulan mulai muncul. Pada fase ini, bulan tidak terlihat karena bagian yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Ini adalah awal dari pola spring tide dan kondisi airnya guris/pasang. Bulan timbul 15 menandai bulan purnama, saat bulan terlihat penuh. Dalam astronomi, bulan purnama terjadi ketika posisi bulan berlawanan dengan matahari, dan sisi bulan yang bercahaya sepenuhnya terlihat dari bumi. Bulan tampak bundar sempurna dan paling terang di langit malam. Ini juga memicu spring tide dengan arus air yang lebih kuat. Dan kondisi air pada bulan timbul 15-17 adalah pasang tertinggi. Bulan timbul 29 atau bulan mati/gelap adalah saat bulan tidak lagi terlihat dan menandai akhir siklus. Dalam astronomi, ini dikenal sebagai fase transisi dari bulan tua menuju bulan baru. Bulan kembali gelap sepenuhnya, dan siklus bulan akan dimulai lagi. Bapak menyebutkan bahwa "bulan timbul 1-15" adalah fase bulan terang, dan "bulan timbul 16-29,5" adalah fase bulan gelap.
Ada 4 kondisi air yang bapak sampaikan. Ada Guris, Surut, Konda dan Gila-gila. Setelah itu, aku merasa perlu memverifikasi pengetahuan ini. Aku pun melanjutkannya dengan browsing, mencari hal-hal terkait dengan bulan dan pasang surut air di internet. Guris adalah kondisi air pasang, yaitu ketika volume air naik atau bertambah. Surut adalah kebalikan dari guris, di mana volume air menjadi berkurang. Konda adalah kondisi air yang pelan dan tenang, biasanya terjadi di antara transisi dari pasang dan surut. Gila-gila adalah kondisi air dengan arus yang sangat kuat dan mudah berubah.
Langkah berikutnya adalah aku menyusun kalender bulan timbul bersama bapak. Kami menggunakan kombinasi pengetahuan tradisional dan informasi ilmiah untuk merumuskan pola pasang surut air. Aku berharap dapat melestarikan warisan ini sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat yang bergantung pada sungai dan laut. Pengetahuan tradisional seperti ini perlu dihargai, dilestarikan, dan disebarluaskan sebagai bagian dari identitas budaya kita yang kaya dan berharga. Dan juga sebagai pembacaan lanjutan, apakah gejala bulan dan arus masih sama, atau ada yang berubah.
Namun ada catatan penting, bahwa pola yang terjadi di sungai cenderung mengalami keterlambatan (delay) akibat pengaruh topografi, aliran air, dan jarak dari sumber laut. Kalender ini kami maksudkan sebagai panduan bagi masyarakat lokal untuk menentukan waktu terbaik melakukan aktivitas di sungai dan laut, seperti menangkap ikan atau memanfaatkan aliran sungai dan laut untuk keperluan lain.
Dari susunan kalender yang aku buat bersama bapak, aku kemudian memikirkan visual yang baik agar lebih mudah dipahami.
Teropong Kain: Teknik Sederhana Yang Menakjubkan
Baju atau kain merupakan alat tradisional yang digunakan oleh komunitas lokal bapak untuk melakukan pengamatan bulan. Aku menyebutnya "teropong kain". Melihat bulan melalui serat kain tipis adalah cara unik yang mempertegas detail bulan, seolah-olah cahayanya melembut dan lebih fokus. Serat kain bertindak seperti filter alami, mengurangi intensitas cahaya yang menyilaukan dan membantu mata menangkap bentuk dan fase bulan dengan lebih jelas.

Meskipun terdengar sederhana, "teropong kain" ini mencerminkan kecerdikan komunitas lokal bapak dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memahami alam semesta. Dan juga hal ini menunjukkan bahwa kearifan tradisional sering kali lahir dari kebutuhan praktis yang dipadukan dengan kreativitas.
Zoom In dan Zoom Out dalam Perjalanan Residensiku
Dalam perjalanan residensiku ini, aku memutuskan untuk menggunakan metode kerja zoom in dan zoom out. Metode zoom in membawaku untuk menyelami pengetahuan lokal melalui tradisi lisan yang diwariskan bapak. Dengan berbicara langsung dengan beliau, aku belajar bagaimana buyutku membaca bulan timbul dan bagaimana pola pasang surut air dipengaruhi oleh fase bulan. Proses zoom in ini memungkinkan aku untuk terhubung secara emosional dengan cerita bapak, memperhatikan setiap detail yang disampaikan, seperti cara beliau menggunakan kain tipis sebagai alat untuk mengamati bulan.
Metode zoom in menunjukkan betapa kayanya tradisi lisan yang dimiliki oleh keluargaku. Ia mengingatkan bahwa pengetahuan semacam ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang cerita, hubungan, dan penghormatan terhadap alam. Tradisi ini mengajarkan aku untuk lebih menghargai warisan buyutku, melihatnya sebagai bagian integral dari identitas diri.
Metode zoom out adalah upaya untuk menempatkan pengetahuan lokal dalam konteks yang lebih luas. Aku mulai dengan mencari informasi tambahan melalui browsing, membandingkan apa yang bapak ajarkan tentang bulan timbul dengan konsep ilmiah modern.Aku menemukan bahwa pola pasang surut yang dijelaskan oleh bapak sesuai dengan prinsip gravitasi bulan yang dipelajari dalam sains modern.
Sebagai bagian dari zoom out, aku meluangkan waktu untuk menggambar sketsa tempat-tempat yang aku kunjungi selama residensi. Aktivitas ini menjadi cara bagiku untuk menjauh sebentar dari semua informasi yang telah aku kumpulkan, memberikan ruang untuk merenungkan hubungan antara tradisi, lingkungan, dan diriku sendiri.
Proses zoom out mengajarkan aku untuk tidak hanya menerima tradisi sebagaimana adanya, tetapi juga untuk melihat bagaimana ia berinteraksi dengan dunia modern. Ini adalah pengingat bahwa pengetahuan lokal tidak terisolasi, tetapi selalu berada dalam dialog dengan perkembangan global. Selain itu, membuat sketsa menjadi terapi visual yang membantu menenangkan pikiran.
Kombinasi zoom in dan zoom out menciptakan dramaturgi yang jelas dalam perjalanan residensi ini. Zoom in membawa kedalaman fokus, mengungkap detail-detail tradisi yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Zoom out, di sisi lain, memberi jarak dan konteks yang memungkinkan aku memahami tradisi ini secara lebih objektif dan menyeluruh. Dramaturgi ini seperti sebuah narasi yang bergelombang, dimulai dari kisah mendalam tentang keluarga dan tradisi, lalu melebar ke semesta yang lebih luas.
Menemukan Kepercayaan Diri Lewat Sketsa dan Instalasi
Residensi ini telah menjadi ruang eksplorasi yang membebaskan sekaligus mendalam bagi diriku. Dalam prosesnya, aku menghadirkan karya-karya yang merepresentasikan perjalanan riset, pengalaman personal, dan refleksi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, khususnya lewat pengetahuan lokal yang diwariskan oleh buyutku. Melalui sketsa hitam putih dan instalasi kalender bulan serta fase pasang surut air, aku menemukan perspektif baru tentang praktik seniku, sekaligus membangun kembali kepercayaan diri dalam berkarya.
Sebelum residensi ini, sketsa adalah sesuatu yang selalu aku anggap kurang menarik dan bahkan menjadi kelemahanku. Aku cenderung berfokus pada proses pewarnaan dalam karya visualku, merasa bahwa itulah inti kekuatan ekspresiku. Namun, residensi ini menjadi momen untuk keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi potensi sketsa sebagai medium utama.

Dalam residensi ini, aku memilih bahan pensil charcoal dan tinta cina. Teknik ini memungkinkan aku untuk mengungkapkan perasaan dan cerita secara langsung, tanpa perlu khawatir tentang keindahan formal atau estetika yang "sempurna." Aku menggambar pemandangan tempat-tempat yang aku kunjungi selama residensi, seperti tepian sungai, batang dan pelabuhan. Garis-garis kasar dari charcoal dan sapuan tinta menciptakan kesan mendalam tentang dinamika alam. Proses ini bukan hanya merekam apa yang aku lihat, tetapi juga menghadirkan suasana dan hubungan emosional dengan lingkungan yang menjadi latar ceritaku.
Salah satu pelajaran terbesar dari eksperimen ini adalah belajar untuk menerima kekurangan dalam karya. Sketsa hitam putih ini menjadi ruang di mana aku bisa bebas dari tekanan untuk menciptakan sesuatu yang sempurna. Sebaliknya, aku lebih fokus pada kejujuran ekspresi, membiarkan cerita tradisi dan pengalaman visualku berbicara lewat garis-garis yang kadang tidak teratur namun penuh makna. Aku menyadari bahwa sketsa adalah fondasi dari setiap ide visual, sebuah langkah awal yang jujur dan spontan.
Selain sketsa, karya instalasi juga menjadi bagian penting dalam residensi ini. Instalasi ini merepresentasikan kalender bulan timbul dan pola pasang surut air, yang aku rumuskan bersama bapak.

Aku menggunakan material sederhana seperti triplek, pipa, kayu, lampu dan kain untuk membuat kalender ini. Di sisi kiri instalasi, ada sebuah lingkaran besar yang memvisualisasikan siklus bulan dengan pola pasang surut yang terjadi di sungai. Karya ini dirancang dengan estetika yang menggabungkan budaya lokal dan tradisi religius keluarga. Tulisan di kalender ini menggunakan penulisan arab, namun mengandung bahasa Indonesia. Penulisan ini biasa dipakai dalam pembelajaran kitab kuning di pesantren. Pemilihan pegon bukan hanya simbol keindahan visual, tetapi juga penghormatan terhadap akar religius keluarga. Instalasi ini tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga sebagai medium edukasi. Pengetahuan tentang pasang surut air yang diwariskan dari buyut ke bapak, dan sekarang ke aku, dihadirkan dalam bentuk visual yang dapat diakses oleh siapa saja. Karya instalasi ini adalah manifestasi dari kombinasi riset, tradisi, dan eksperimen visualku selama residensi.
Meski terlihat berbeda, sketsa dan instalasi dalam residensi ini sebenarnya saling melengkapi. Sketsa menjadi cara untuk merekam dan merenungkan, sementara instalasi adalah medium untuk berbagi pengetahuan lokal bapak.
Why should the head of women in particular be considered so dangerous that it must be made to disappear?
This is no more than the age-old patriarchal struggle over women's heads, the fear that they might begin to think and throw off the bonds of slavery, of an inferiority enforced on them in all religions and in all societies.
—Nawal el Saadawi, "War Against Women and Women Against War: Waging War on the Mind."
“When I was a child, the word God for me meant justice or freedom or love. How did it become a sword over my head, or a veil over my mind and face? — A Daughter of Isis, Nawal El Saadawi